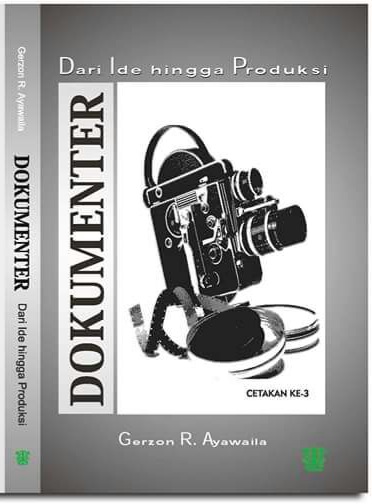Gerzon Ron Ayawaila
Rabu, 24 Agustus 2022
Senin, 07 Februari 2022
Media Film Sebagai Metode Penelitian
Pidato Ilmiah Dr. Gerzon R. Ajawaila, M.Sn.
Media Film Sebagai Metode Penelitian
Sekarang ini sulit menemukan wujud seni tradisi lokal yang terbebas dari pengaruh eksternal, semisalnya intervensi agama, politik dan ekonomi.
Contoh umum adalah, isu pelestarian aset budaya lokal, menyebabkan orisinalitas ritual tradisi milik masyarakat adat “dimodifikasi” menjadi program seni pertunjukan untuk kepentingan pariwisata.
Keresahan pada permasalahan ini menjadi motivasi saya untuk mencoba melestarikan seni pertunjukan tradisi melalui media film.
Pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya akan memaparkan secara ringkas tentang metode penelitian etnografi dengan memfungsikan kamera film sebagai alat pencatat data visual, yang menghasilkan suatu penciptaan karya film Etnodokumenter, sebagai bentuk kreatif alihwahana.
Kesan atau ilusi gerak tercapai dan pada awal penemuan film di tahun 1895 di Prancis oleh Lumiere Bersaudara, dan penciptaan ini menjadi tonggak sejarah yang penting bagi lahirnya film. Selanjutnya film memiliki dua bentuk utama, yakni film fiksi dan film dokumenter.
Film Dokumenter itu sendiri terus berkembang hingga kini, yang dengan berbagai jenisnya telah mencoba mengungkap realitas dari berbagai bentuk, gaya dan perspektif.
John Collier, JR. menulis sebuah buku menarik yang berjudul “Visual Anthropology: Photography AS A Research Method” inti buku ini adalah bagaimana fotografi dapat merekam manusia dan lingkungannya sebagai subyek penelitian, maka dari foto-foto yang terekam tersebut dapat memperlihatkan berbagai aspek kehidupan manusia yang sedang diamati.
Namun film sebagai medium bersifat tabula rasa, yaitu bagaikan kertas putih dan tergantung pada kita, soal bagaimana menggunakan kertas kosong ini. Jadi ada lompatan dari fotografi sebagai metode penelitian etnografi visual menjadi film sebagai piranti metode penelitian.
Saya ingin berbagi pengalaman ketika melakukan penelitian etnografi tentang seni musik tradisi Tarawangsa, di Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat.
Dimaksud dengan musik sakral dapat terlihat pada sejumlah sesajian serta doa-doa yang dilakukan juru kunci dan tetua adat, sebelum musik dimainkan dan dipertunjukan.
Saya telah melakukan berbagai pengamatan pada beberapa seni tradisi, secara deduksi opsi ketertarikan saya tertuju pada seni pertunjukan dan ritual tradisi milik masyarakat Rancakalong. Seni pertunjukan musik tradisi ‘Tarawangsa’ dari Rancakalong, tidak sekedar pertunjukan seni musik tradisi tetapi memiliki makna yang dalam sebagai musik yang menjadi sentral atau bagian sangat penting pada upacara tradisi Ngabubur dan Ngalaksa masyarakat Rancakalong.
Musik Tarawangsa dipertunjukan sebagai syarat bagi masyarakat Rancakalong melaksanakan upacara tradisi Ngabubur yaitu membuat penganan bubur dan Ngalaksa membuat penganan laksa. Upacara tahunan ini dilakukan untuk menghormati Dewi Sri (dewi kesuburan padi), dan masyarakat Rancakalong menyebutnya Nyi Pohaci.
Asal kata Tarawangsa, ta=tatabeuhan, wa=wali, sa=salapan yang disatukan menjadi arti kata tatabeuhan wali salapan.
Musik Tarawangsa dimainkan oleh dua orang pemusik menggunakan dua instrumen musik yaitu Tarawangsa (yang bentuknya seperti rebab) dan Jentreng (yang bentuknya seperti kecapi).
Suara musik Tarawangsa yang oleh telinga awam terdengar seperti berulang-ulang dengan melodi dan ritme yang sama, dapat merangsang emosi dan perasaan kita yang larut hingga mengalami trans.
Pengalaman studi doktoral saya meneliti dan memproduksi film etnodokumenter yang berjudul Tarawangsa. Film yang berdurasi 36 menit ini mengetengahkan tema seni pertunjukan musik tradisi masyarakat Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat.
Tim saya bertiga (2 juru kamera dan 1 asisten) mengunjungi lokasi pada awal tahun 2016, kedatangan kami bersamaan dengan tradisi Ngabubur. Kami membawa kamera sederhana (handycam) sebagai piranti perekam pada upacara tersebut yang berlangsung selama dua hari. Rekaman dengan kamera sederhana ini sangat berguna untuk mencatat data dan urut-urutan upacara, termasuk pertunjukan musik Tarawangsa.
Pada tahun 2017 saya bersama tim produksi, yaitu 2 juru kamera dan 1 asisten tehnik kembali ke Rancakalong tepatnya ke desa Cibunar, untuk merekam upacara Ngalaksa yang dilangsungkan setelah musim panen dibulan juli. Pada syuting kedua ini kami membawa dua kamera dan membuat dokumentasi data visual selama 15 jam. Di tahun yang sama kami kembali lagi ke Rancakalong untuk merekam upacara Ngabubur yang dilaksanakan pada penanggalan 10 suro, yang dilaksanakan di desa Nagarawangi.
Kemudian ditahun berikutnya yaitu 2018, kembali kami mendatangi Rancakalong untuk merekam upacara Ngabubur pada desa yang berbeda yaitu di desa Rancakalong.
Perlu diketahui upacara Ngabubur dilakukan oleh satu Rurukan atau dusun selama 2 hari sedangkan upacara Ngalaksa dilaksanakan oleh gabungan 5 Rurukan selama 5 hari, bertempat di sebuah pendopo besar terletak di desa wisata.
Kemudian pada pertengahan tahun 2019 saya membuat rekaman khusus pertunjukan musik tradisi Tarawangsa di studio dengan menggunakan multi kamera, hal ini dilakukan untuk mendapatkan suara jernih dari musik Tarawangsa. Di lokasi upacara suara musik Tarawangsa sangat dominan, hal ini difungsikan sebagai tanda adanya kegiatan ritual kepada seluruh warga, sekaligus memberikan pengaruh psikologis pada keseluruhan prosesi ritual.
Film Etnodokumenter dapat dikatakan sebagai sebuah hasil proses interdisiplin antara metode etnografi observasi partisipan dari teori Bronislaw Malinowski, dipadukan dengan gaya bertutur dokumenter observasional. Seperti dikatahui gaya bertutur observasional tersebut merupakan hasil kajian Bill Nichols pada gaya produksi Cinema Verite yang dikembangkan sineas Perancis Jean Rouch di tahun 60an.
Penggarapan etnodokumenter mengacu pada metodologi etnografi/antropologi, kemudian dipadu dengan konsep sinematografi, karena karya etnodokumenter adalah peleburan dari disiplin ilmu etnografi dan dokumenter. Etnodokumenter khusus menggarap seni tradisi lisan maupun tulisan, sedangkan film dokumenter tentunya dapat mengetengahkan berbagai masalah kehidupan baik tradisi maupun modern bahkan hingga posmodern.
Analogi perspektif naturalistik diterapkan dalam garapan film “Tarawangsa”, agar secara maksimal mampu mengeksplorasi semua fenomena dan merepresentasikannya secara utuh dan kontekstual. Oleh karenanya, pendekatan lain yang selaras diterapkan adalah perspektif emik, yang mengutamakan sudut pandang subjek pelaku tradisi, kedua teori ini merupakan metode dasar bagi pembuatan film etnodokumenter Tarawangsa sebagai bungkus dari pendekatan realistik.
Emmanuel Levinas menyatakan bahwa etika positif harus dikelola dengan jernih agar mampu menghindari visi subyektif yang dapat membuat kegagalan pada proses penelitian yang ingin memahami sudut pandang masyarakat adat.
Para pionir pembuat film dokumenter etnografi seperti Robert Flaherty, Robert Gardner dan John Marshal telah terjebak dengan perspektif etik mereka, sehingga etika etnosentrisme membuat mereka gagal dalam merepresentasikan kebenaran dari sudut pandang masyarakat pemilik tradisi.
Menjadikan kamera sebagai media observasi partisipan akan lebih objektif apabila dipertegas dengan perspektif emik, yaitu berdasarkan sudut pandang subjek sebagai pemilik tradisi.
Kamera merekam setiap ungkapan yang memperlihatkan makna simbol suatu peristiwa budaya dalam konteks ritual tradisi.
Perspektif emik mengandung nilai etika, dan dapat mengindari bias subjektif yang akan menghambat objektifitas pada realitas, seperti adanya persepsi etnosentrisme yang tidak disadari.
Proses penelitian dan penciptaan karya film etnodokumenter Tarawangsa yang saya lakukan selama tiga tahun, seakan melakukan penelusuran makna simbol dan ekspresi suatu kearifan lokal.
Makna atau simbol dari seni pertunjukan tradisi lisan, saya yakini akan lebih transparan dengan memfungsikan kamera sebagai media observasi partisipan. Kamera film dapat mengumpulkan data laporan penelitian yang akurat, seperti yang diakui oleh antropolog Margaret Mead, bahwa alat kamera film atau foto dapat menjadi metode baru untuk kepentingan penelitian etnografi.
Berangkat dari konsep kamera sebagai media observasi partisipan yang khusus untuk merekam ritual tradisi seni pertunjukan, maka menggunakan tipe lensa kamera harus dengan ukuran lensa sudut lebar. Perekaman adegan dilakukan tanpa mengubah-ubah ukuran lensa maupun ukuran shot.
Selain itu, menggunakan teknik zooming merupakan hal yang tabu bagi penggarapan film etnodokumenter, karena itu merupakan tindakan manipulatif terhadap makna dari realitas imaji.
Hal yang sulit adalah secara konstan mampu menghindari pembingkaian subjektif, karena naluri estetika sinematografi kadang tanpa disadari telah melakukan pembingkaian terhadap objek dan subjek yang hadir didepan lensa kamera.
Proses editing pada film ‘Tarawangsa’, yaitu menyunting dan menyusun berdasarkan struktur kronologis. Pada penciptaan karya ini, ada tiga produksi film, yaitu pertunjukan musik Tarawangsa, upacara tradisi Ngalaksa serta Ngabubur, dan ketiga produk ini akan diproyeksikan secara bersamaan pada tiga layar yang terpisah. Eksperimentasi sajian pada tiga layar ini menuntut konsentrasi pada proses sinkronisasi antara gerak tubuh para pengibing dengan alunan musik Tarawangsa. Suatu penyajian di layar tidak sekedar memperlihatkan gambar-gambar bergerak sebagai susunan kronolgis, tetapi proyeksi pada tiga layar ini dapat dimaknai sebagai suatu panggung seni pertunjukan musik Tarawangsa dalam tradisi Ngabubur dan Ngalaksa.
Pilihan untuk mengutamakan keindahan atau kebenaran, estetika atau fakta, merupakan pilihan yang tidak mudah. Konsep garapan Film etnodokumenter Tarawangsa, mengutamakan perspektif realistik dan dipercaya bahwa imaji objek kreatif yang disajikan sudah memberikan makna estetikanya sendiri.
Kesimpulannya, film dapat berbentuk film fiksi, film dokumenter, maupun eksperimental. Namun film sebagai media dapat menjadi piranti metode penelitian yang menghasilkan dokumentasi data visual. Kumpulan data visual ini dapat dikemas sebagai bagian dari karya utuh film etnodokumenter.
Maka, perumusan dalam usaha mengetengahkan suatu ekspresi dengan persepsi yang tidak sesuai kaidah umum, perlu argumentasi yang dapat diterima sebagai suatu proses ide kreatif. Suatu hal yang harus dilakukan dengan argumentasi logika adalah bagaimana persepsi yang ada dapat ditransformasikan, dan publik penonton dapat memahaminya.
Sebuah konsep eksperimentasi seni harus memiliki nalar untuk memahami makna kreativitas garapan yang dapat memberi ruang bagi sudut pandang apresiasi baru.
Terimakasih
Jakarta, 14 Desember 2021
Hormat saya,
Gerzon .R. Ajawaila
Jumat, 25 September 2020
Abstrak
Film Kebenaran atau Kebenaran Film (Gerzon.R.Ayawaila)
Setelah bersaudara Lumiere menemukan perangkat tehnologi film, maka ini dianggap merupakan era kelahiran bentuk seni modern. Film sebagai bentuk seni yang paling bungsu, lahir menyusul bentuk seni lain yang sudah ada sejak abad sebelum masehi. Seni film sendiri kemudian beranak pinak dan berproses mencari jatidirinya malalui bentuk dan gaya baru. Ini dapat dilihat pada munculnya beberapa gaya, aliran serta bentuk, baik bertujuan eksperimental maupun kemudian disahkan dengan istilah kontemporer sesuai ruang dan waktunya. Satu hal yang jelas dapat diamati bahwa semua gerak maju ini bertujuan mencari sesuatu yang baru, meski usaha inovasi tersebut ada yang memang bergerak maju kedepan, tetapi ada pula yang tanpa sadar hanya terpaku pada suatu lingkaran interpretasi dan kemudian memaksakan untuk hadir kembali dengan tambahan bumbu penyedap.
Mengulas balik tradisi gaya dan bentuk pada dunia film baik fiksi maupun non-fiksi, yang kemudian dikenal dengan gerakan free cinema, neo-realis, nouvelle vague, terahir ketika kamera diproduksi dengan ukuran lebih kecil, praktis dan ringan, maka lahirlah cinema verite. Membicarakan kemunculan Cinema Verite, tentunya tidak semata karena diproduksinya kamera yang lebih kecil dan ringan, akan tetapi sebuah nama Dziga Vertov yang meletakan dasar teori mata film (kino eye) pada tahun 1919, berkaitan ketika perang dunia keII usai, teori Vertov mulai dikenal sekaligus dikaji oleh para sineas dokumenter. Setelah Vertov di tahun 1922 memproduksi sejumlah film jurnalnya yang dilabeli dengan nama Kino Pravda (film kebenaran) maka label ini pun dipakai para sineas dokumenter Perancis dengan nama Cinema Verite yang memiliki arti sama yaitu ‘film kebenaran’.
Terminologi ini mulai menarik perhatian para pengamat maupun jurnalis ketika dua sineas dokumenter Perancis, Jean Rouch dan Edgar Morin mempublikasikan filmnya di tahun 1962 dengan judul Chronique d’un ete. Rouch dan Morin menggunakan terminologi cinema verite sebagai strategi promosi bagi film mereka, sekaligus menyatakan bahwa film mereka itu merupakan sebuah karya dokumenter yang khusus didedikasikan kepada Dziga Vertov sebagai salah satu bentuk penghormatan mereka, karena Dziga Vertov dianggap telah memberikan pencerahan dan inspirasi pada mereka. Karisma Vertov dengan teori kino
eye/kino pravda, tidak saja memukau kedua sineas Perancis ini, tetapi juga sejumlah sineas dokumenter diberbagai belahan dunia. Film kebenaran dianggap seperti memberikan suatu formula baru pada perkembangan teori film dokumenter, yang dijabarkan pada konsep filosofis penyutradaraan (directing concept).
Apa itu Cinema Verite ?. Hingga sekarang cinema verite memberikan pemahaman konsep yang merangsang diskusi bahkan perdebatan alot, sehingga para pengamat mengintrepretasikannya dengan bermacam ulasan komentar dan kritik. Cinema Verite masih dianggap memberikan suatu pemahaman dengan berbagai tafsiran yang diakui belum menemukan happy ending. Disisi lain tentunya ini menandakan betapa merangsangnya pemahaman cinema verite sehingga setiap literatur dokumenter akan menggunakannya sebagai acuan bahasan utama, dan menjadi referensi teori pada setiap konteks yang akan diketengahkan.
Namun pada akhirnya Jean Rouch mengakui bahwa Film Kebenaran adalah Kebenaran dari film itu sendiri, sehingga berbeda dengan kebenaran dari fakta peristiwa yang terjadi dihadapan lensa kamera film. Sama seperti yang dikatakan Vertov dengan kino eye nya bahwa, apa yang terlihat di layar, itu bukan sebuah kebenaran objektif, tetapi sebuah kebenaran subjektif, hasil dari rekaman lensa kamera sebagai Mata Film.